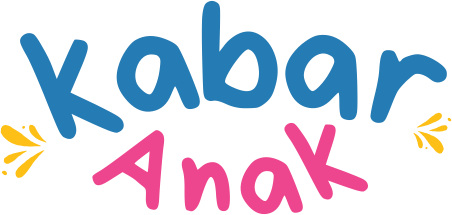Gambar Generate
Gambar Generate
Setiap hari, jam 04.00, alarm ponsel Irfan berbunyi pelan. Bukan karena ia suka bangun pagi—tapi karena hidup tidak pernah menunggu orang yang masih ingin tidur.
Ia bangun di kamar sempit, menahan dingin lantai, lalu berwudu cepat. Di sela-sela sujud, ia sering lupa harus minta apa. Bukan karena tidak punya harapan, tapi karena terlalu banyak yang harus ditanggung. Setelah itu, ia menyiapkan seragam, menyeduh kopi hitam murah, dan memastikan dompetnya berisi cukup untuk ongkos.
Pukul 05.00 ia sudah di jalan.
Pagi ia bekerja sebagai kurir—mengantar paket, menghadapi macet, panas, hujan, dan wajah-wajah yang kadang ramah, kadang tak peduli. Siang ia lanjut sebagai helper di gudang—angkat barang, hitung stok, dan menelan lelah sambil berdiri. Malam, saat orang lain pulang, ia masih menyapu dan bersih-bersih di warung makan dekat kos. Tangannya bau sabun, punggungnya pegal, matanya perih.
Kadang ia pulang jam 23.30. Kadang lewat tengah malam.
Di kos, ia duduk sebentar di tepi kasur, menatap telapak tangannya yang kasar. Pikirannya selalu sama: “Yang penting besok masih bisa kerja. Yang penting ibu di rumah tidak kekurangan.”
Ibunya sering telepon, suaranya pelan karena tidak mau terlihat membuat anaknya sedih.
“Nak, jangan dipaksakan. Kamu itu juga harus istirahat.”
Irfan hanya tertawa kecil.
“Tenang, Bu. Irfan kuat.”
Padahal, tidak selalu.
Ada malam-malam di mana ia diam saja di sudut kamar, menahan sesak yang tidak bisa diberi nama. Ia merasa hidup seperti roda yang terus berputar, tanpa pernah benar-benar sampai.
Namun Irfan punya satu kebiasaan kecil yang tak pernah ia tinggalkan: setiap menerima gaji atau upah harian, ia menyisihkan sedikit—sangat sedikit—lalu memasukkannya ke amplop cokelat tanpa tulisan.
Kadang hanya lima ribu. Kadang sepuluh. Kalau rezekinya agak longgar, ia masukin lima puluh.
Temannya pernah melihat amplop itu dan bertanya sambil bercanda,
“Buat apaan sih, Bu? Nabung nikah?”
Irfan tersenyum. Senyumnya seperti orang yang menyimpan rahasia paling lembut.
“Bukan.”
Ia tak pernah bilang. Bahkan kepada ibunya.
Karena ia takut kalau mengucapkan, doanya terdengar terlalu besar untuk orang seperti dia.
Hari demi hari lewat. Bulan berganti. Lelahnya menumpuk, tapi ia tetap berjalan. Sampai suatu sore, ia jatuh sakit di gudang. Badannya panas, dadanya berat. Ia tetap memaksa masuk kerja, tapi kepala berputar, pandangan gelap.
Ia pulang lebih cepat, meringkuk di kasur, menggigil. Dalam demam, ia membuka ponsel dan tanpa sengaja muncul video orang-orang thawaf. Suara talbiyah pelan—hampir seperti bisikan.
Irfan menangis. Tanpa tahu kenapa.
Ia bukan menangis karena sakit. Ia menangis karena merasa… sudah terlalu lama ia jauh dari tenang.
Dalam kondisi lemah itu, ia ambil amplop cokelatnya. Ia buka. Uang di dalamnya tidak banyak. Tapi terasa sangat berat—berat karena di setiap lembar ada keringatnya, ada langkahnya, ada waktu tidurnya yang hilang, ada lapar yang ia tahan, ada lelah yang ia pendam.
Irfan menatap amplop itu lama.
Lalu ia berbisik, suaranya pecah,
“Ya Allah… kalau Engkau izinkan… aku pengen jadi tamu-Mu.”
Malam itu, ia telepon ibunya. Suaranya masih serak.
“Bu… Irfan kangen.”
Ibunya terdiam sebentar, lalu suaranya bergetar.
“Ibu juga kangen, Nak. Ibu doakan kamu selalu.”
Irfan menelan air mata.
“Bu… kalau suatu hari Irfan bisa… Irfan pengen ngajak Ibu ke Tanah Suci.”
Di seberang, hening lama. Lalu terdengar tangis yang ditahan-tahan.
“Ya Allah… Nak… jangan ngomong begitu… Ibu… Ibu cuma pengen kamu sehat.”
Irfan tersenyum dalam tangis.
“Biar Irfan yang kerja, Bu. Biar Irfan yang usaha. Ibu tinggal doa.”
Esoknya, hidup tidak langsung berubah. Ia tetap kerja. Tetap macet. Tetap panas. Tetap capek.
Tapi sejak hari itu, Irfan bekerja dengan satu hal baru di dadanya: bukan ambisi, bukan gengsi—melainkan harapan yang lembut.
Setiap kali ia lelah, ia membayangkan satu momen: berdiri di depan Ka’bah, bukan sebagai orang kaya, bukan sebagai orang besar—tapi sebagai hamba yang akhirnya pulang setelah bertahun-tahun berjuang.
Dan di akhir hari, saat ia memasukkan uang kecil lagi ke amplop cokelat itu, Irfan selalu berbisik pelan, seperti menulis janji ke langit:
“Ya Allah… pelan-pelan saja. Yang penting aku menuju.”
Semoga kita bisa menuju rumah Allah melalui baitullah.co.id
Tags:
Zeta
Seorang penulis yang fokus pada dunia anak dan parenting. Gemar berbagi tips pola asuh, edukasi anak, serta inspirasi keluarga yang penuh cinta.
Artikel Lainnya
Viral Ayah Aniaya Anaknya yang Masih Balita, Pelaku Kabur Usai Video Menyebar
- 17 Oktober 2025
- 3 months ago
5 Cara Mengobati Luka Berair agar Cepat Kering yang Efektif
- 29 Desember 2025
- 1 month ago